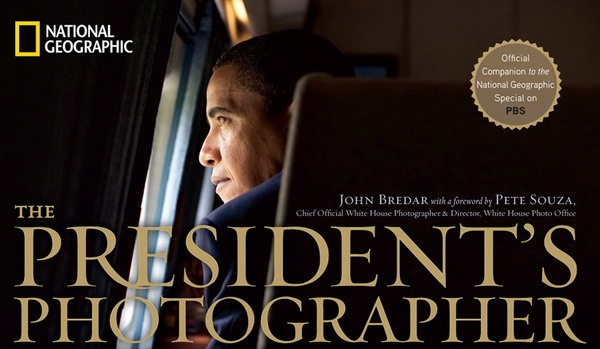|
| Foto : James Nachtwey |
Ada begitu banyak anak-anak di Afghanistan, tapi hanya secuil masa kanak-kanak di sana ..
Jalur sutra melintasi Afghanistan, dan Provinsi Bamiyan merupakan “jembatan” yang menghubungkan pusat-pusat kebudayaan dan perdagangan jagatraya: Cina, India, dan Kekaisaran Romawi. Sejak abad ke-5 situs-situs Budha berukuran raksasa menjadi identitas Bamiyan – dan Afghanistan. Afghanistan yang kini dikategorikan salah satu negeri termiskin pernah menggoda Alexander Agung dan Genghis Khan. Di Bamiyan kaum Mongol meninggalkan jejaknya: etnis Hazara. Orang-orang Hazara memiliki ciri-ciri orang Mongolia, bermata sipit, berwajah mirip orang Cina.
Etnis Hazara adalah penganut Muslim Syiah, jumlahnya tak lebih dari 9% dari keseluruhan penduduk Afghanistan. Tapi anak Afghan bernama Amir tidak pernah mengenal apapun mengenai kaum Hazara dari buku-buku sekolah dan tidak seorang gurupun membahasnya. Assef, seorang anak lain, menjelaskan situasi ini, “Afghanistan adalah negeri bangsa Pashtun. Kita adalah orang-orang Afghan sejati, orang-orang Afghan murni.” Bagi Assef, Hazara mengotori negeri dan darah Afghanistan.
Amir maupun Assef beretnis Pashtun. Penindasan orang Pashtun terhadap kaum Hazara tercatat dalam sejarah yang seolah tak memiliki bab akhir. Pada abad ke-19 para Hazara mencoba melawan tapi kaum Pashtun menghentikan perlawanan mereka dengan “kekerasan yang tidak terkatakan.”
Dari buku sejarah tua berdebu milik mendiang ibunya Amir mengetahui pembantaian itu, rumah mereka dibakar, ditendang dari tanah mereka, dan perempuan-perempuannya direndahkan. Assef tak pernah ingin memangkas kebenciannya, ia menumbuhkan pemujaan terhadap Hitler dan terang-terangan mengungkapkan kekagumannya pada apa yang disebut ethnic cleansing.
Tapi Amir tinggal di pekarangan yang sama dengan Hassan yang Hazara. Baba – begitu panggilan Amir pada ayahnya – seorang laki-laki Afghan terhormat. Ia cerdas, berwawasan dan lebih terbuka ketimbang kaumnya, meskipun dalam beberapa hal tetap dikotomis tapi jauh dari kolot. Kediamannya merupakan rumah terindah di distrik Wazir Akbar Khan, kompleks mewah di sisi utara Kabul. Ayah Baba, kakek Amir, berteman dengan Raja Nadir Shah. Dan Baba menikahi seorang wanita yang keindahannya disempurnakan intelektualitasnya.
Sementara Ali, ayah Hassan, adalah yatim-piatu yang ditampung kakek Amir setelah kedua orangtuanya tewas digasak pengemudi teler. Ali dan Baba tumbuh bersama. Saat dewasa Ali melayani keluarga Baba hingga 18 tahun. Kedekatan Baba dan Ali melatari hubungan Amir dan Hassan. Namun keterikatan dua bocah itu mengandung dimensi lebih dalam: sama-sama kehilangan ibu dan menyusu dari payudara yang sama.
Mereka bersahabat tapi juga berjarak. Amir anak majikan dan Hassan anak pelayan; Amir Pashtun, Hassan Hazara; Amir Muslim Sunni, Hassan Syiah. Meski hanya beberapa langkah dari pintu rumahnya Amir tidak cukup terbiasa mengunjungi rumah Hassan, sebuah pondok kecil berdinding tanah liat.
Ali dan Hassan memiliki tanda fisik yang seolah menggenapkan mereka sebagai warga kelas dua. Ali pincang karena polio, Hassan sumbing. Sebagaimana orang Afghan yang gemar melemparkan joke seringkali ayah-anak ini dijadikan lelucon. Tapi mereka berdua menjalani hidup tanpa niatan mengguncang tatanan. Hal paling menonjol dari mereka tapi pernah tidak ditonjol-tonjolkan adalah kesetiaan dan penyerahan diri.
 |
| Foto : James Nachtwey |
The Kite Runner adalah kisah pengembaraan yang panjang dua bocah di tengah carut-marut kehidupan yang tidak pernah dirancangnya. Di Afghan semua itu terjadi tanpa tedeng aling-aling: Baba laki-laki yang berdaya tapi satu gerakan matanya bisa berarti memuluskan terjangan peluru Russia di dadanya. Kenyataannya memiliki seorang ayah di Afghanistan adalah kemewahan.
Novel ini bukan soal dampak invasi atau ketidakberdayaan di bawah kaki orang lain. Bukan cerita soal proses titik-balik seperti Ahmed Shah Massoud yang meninggalkan sekolah untuk menjungkirbalikkan keperkasaan Soviet dengan taktik gerilya dan nantinya menjadi hantu pegunungan yang menyebar teror pada kaum Taliban. Khaled Hosseini, penulisnya, membawa kita menerobos permukaan dan menelusuri lembah-lembah kepedihan Afghanistan. Amir digasak pergolakan di sekellilingnya dan di dalam dirinya sendiri.
Beberapa peristiwa yang terjadi sebelum perang menjerumuskan Amir pada kegamangan dan ketakutan yang abadi. Amir tidak seperti Baba yang independen dan kokoh. Amir selalu bergetar menghadapi Assef yang mampu mencuilkan kuping anak lain. Saat Assef sungguh-sungguh mengancamnya justru Hassan yang menjadi tameng. Hassan yang Hazara. Hassan orang terdekatnya yang tak pernah benar-benar dianggapnya teman (“Dia bukan temanku! Dia pelayanku!” teriaknya dalam batin). Hassan yang tidak tega menimpuk anjing tapi akan melakukannya jika Amir menginginkannya.
Hassan mengarahkan katapel pada Assef dan Assef tahu bidikannya tidak akan luput. Assef mundur, Amir selamat. Tapi beberapa saat kemudian Assef membalas Hassan dengan kekejian yang tidak terbayangkan. Amir melihatnya – dan mengambil pilihan yang akan menjadi mimpi kelam sepanjang hidupnya. Keputusan ini sesederhana mengambil jalan ke kiri atau ke kanan namun konsekuensinya tidak pernah sederhana. Pilihan adalah pijakan. Langkah berikutnya menyerupai efek domino. Inilah bagian novel paling miris, paling menyesakkan bagi pembacanya. Simpel, karena sebagian besar dari kita akan melakukan hal yang sama dengan Amir.
 |
| Foto : Alexandra Boulat |
Sejarah melarikan Amir ke Amerika. Ke negeri yang mengkhianati Afghanistan.
Demi memenangkan Perang Dingin Jimmy Carter dilanjutkan Ronald Reagan menyemangati mujahidin dengan hibah yang nilainya mencapai tigajuta dollar. Dana itu tidak semuanya diterima pejuang Afghan. Toh mujahidin tidak lelah-lelahnya melesakkan hantaman ke pasukan Soviet. Soviet akhirnya limbung dan keluar dengan kepala tertunduk.
Tembok Berlin kemudian runtuh, Eropa Timur lepas dari cengkeraman Moskwa, Soviet terburai. “Afghanistan adalah alasan jatuhnya komunisme!” tandas Ahmed Shah Massoud. Wall Street Journal menyebut Massoud sebagai “Orang Afghan yang memenangkan Perang Dingin”.
Afghanistan merayakan kejayaannya. Tapi kedamaian tidak juga berpihak. Kelompok politik yang didukung Pakistan menjadi duri dalam daging. Anak-anak muda radikal yang mengklaim diri sebagai pembebas dengan menerapkan hukum secara ekstrem memaksa Massoud melepas kursi Menteri Pertahanan.
Didukung sukarelawan yang merupakan kombinasi gerilyawan dan petani si Singa dari Panjshir itu mengaum dari celah-celah pengunungan. Kekuatan baru menguasai Kabul dan tiba-tiba menjadi oportunis yang menakutkan. Awan hitam kembali ke Afghanistan tapi Amerika tidak berhasrat lagi menyingkirkannya.
Amir di San Francisco dan Hassan telah pulang ke Bamiyan saat situs-situs Budha yang dianggap berhala oleh Taliban dijadikan serbuk pasir oleh pasukan tank dan gempuran dinamit. Musik dan televisi ditabukan. Tidak ada lagi kompetisi layang-layang yang selama ini menjiwai anak-anak Afghan dan pernah membawa Amir bersama Hassan mencapai puncak kebahagiaan seorang bocah.
Tubuh tanpa nyawa yang tergantung di tengah pemukiman adalah pemandangan sehari-hari. Penguburan jadi rutinitas. Kaum terpelajar dan akademisi mengemis dengan tubuh sebau bangkai. Perempuan terkunci di rumah mereka sendiri, tidak boleh sekolah, tidak boleh sakit karena layanan medis untuk mereka dilarang. Anak-anak bermain dengan perut merintih dan keesokan harinya ada di antara mereka yang dikuburkan. Seorang bayi lahir, tapi hanya beberapa jam kemudian sudah menjelma malaikat yang gamang.
Amir telah menjadi laki-laki bermartabat di Amerika. Ia menikahi putri Jenderal Iqbal Taheri yang terhormat. Ia kini bagian dari Amerika. Massoud berteriak-teriak bahwa masalah di Afghanistan hanyalah simpul dari masalah global yang juga akan menerjang Amerika – tapi Rambo yang dulu bersuara lantang dengan bibir menceng kini juga tuli. Amir malah sudah lebih dulu menutup kupingnya, membutakan hatinya.
Rahim Khan, laki-laki Pakistan partner bisnis dan sahabat Baba – salah satu karakter paling menarik dalam novel ini – berdiri persis di depan pintu batin Amir. “Ada jalan untuk kembali menuju kebaikan,” ketuknya.
Amir tinggal melangkah ke seberang untuk melakukan penebusan. Di sana ada Assef, ada Farid yang labil, tapi juga ada Wahid yang senantiasa teguh dan teduh. Di sana pertandingan sepakbola diselingi eksekusi rajam. Ada direktur panti asuhan yang menjual anak-anak asuhnya untuk membelikan makanan bagi anak-anak lainnya. Di sanalah Hassan selalu bercerita tentang Amir pada Sohrab putranya.
The Kite Runner kaya dan detail. Suatu “emotional journey” yang sentuhannya sedemikian mendalam. Sebagian kecil dari novel ini memang berkembang seperti alur film Amerika, bergerak cepat dan setiap elemen mengandung kejutan. Sebagian kecil lainnya terombang-ambing dalam usaha penebusan dan pemahaman. Tapi pada dasarnya novel pertama dr. Khaled Hosseini ini telah memperlihatkan “indahnya kehidupan di sebuah negara kacau-balau”.
Massoud yang rajin membaca Quran dan buku-buku puisi akhirnya gugur oleh bom bunuhdiri yang tricky. Dua hari kemudian, 11 September 2001, Amerika dilumpuhkan terjangan teroris. Tapi Hassan dan Amir telah memberikan aksentuasi yang kita butuhkan dalam kehidupan yang ringkih ini.
 |
| Foto : James Nachtwey |